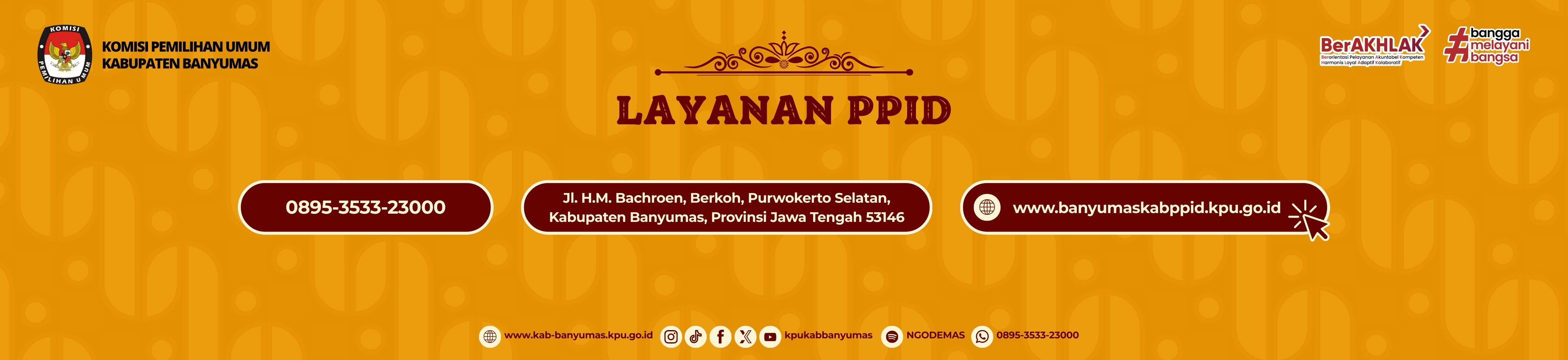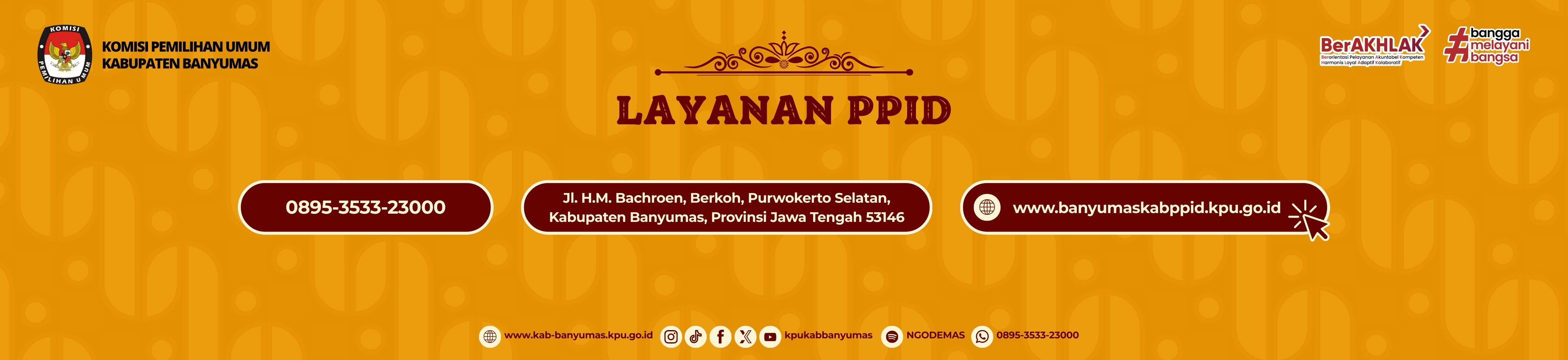Evaluasi Beban Kerja Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan 2024
Oleh : Dwi Rindra T
Beban kerja badan adhoc Pemilu merupakan gabungan antara persepsi seberapa berat tugas-tugas badan adhoc dan seberapa banyak resources dan waktu yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut.
Berbeda dari pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 maupun Pemilihan Serentak Tahun 2020, pembentukan badan adhoc Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 tidak lagi didasarkan pada regulasi Peraturan KPU (PKPU) No. 3 Tahun 2015 untuk badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan PKPU No. 3 Tahun 2018 untuk badan adhoc Penyelenggara Pemilu. Pembentukan badan adhoc Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 didasarkan pada PKPU No. 8 Tahun 2022 yang merupakan hasil evaluasi terhadap regulasi sebelumnya. Selain hasil evaluasi, regulasi terbaru merupakan kodifikasi dari regulasi sebelumnya yang memisahkan antara badan adhoc Penyelenggara Pemilu dengan badan adhoc Penyelenggara Pemilihan. Kodifikasi regulasi menjadi penting untuk menyederhanakan dan menyerasikan regulasi dan mempermudah penguasaan regulasi tersebut.
Hasil evaluasi ini dapat terlihat nyata misalnya pada penurunan angka kasus badan adhoc yang sakit dan meninggal dunia pada badan adhoc. Pada Pemilu Tahun 2019, kasus badan adhoc meninggal secara nasional menyentuh angka yang dramatis, yang memicu respons masyarakat luas akan buruknya manajemen SDM kepemiluan kita. Jumlah badan adhoc yang sakit dan meninggal serta mendapatkan santunan kecelakaan kerja pada Pemilu 2019, berdasarkan data Kemenkeu adalah sebanyak 798 orang yang sakit dan 722 orang yang meninggal.
Sementara pada Pemilu 2024, angka kasus meninggal menurun pada jumlah 181 orang, meskipun angka kasus sakit meningkat drastis pada jumlah 4.770 orang. Pada Pemilihan 2024, sejumlah 183 orang meninggal dan 479 orang sakit. Angka kasus pada Pemilihan 2024 semakin menunjukkan angka yang positif, meskipun belum dapat dikatakan yang terbaik. Namun, kita patut bersyukur dengan hasil yang dicapai ini, yang menunjukkan keseriusan KPU dalam mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 yang menyedihkan.
Pada gilirannya, kita seharusnya tidak berpuas diri atas capaian saat ini. Evaluasi masih perlu dilakukan untuk mengambil pembelajaran yang sudah berjalan baik serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi. Apakah beban kerja badan adhoc Pemilu sudah sesuai dengan kompetensi dan kapasitas SDM badan adhoc yang dibentuk?
Beban Kerja Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan 2024
Badan adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan merupakan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat adhoc yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS. Badan adhoc di tingkat kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS), di tingkat TPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bersama Petugas Ketertiban TPS, serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dibentuk berdasarkan TPS.
Skala Beban Kerja Badan Adhoc
Beban kerja dapat dipahami sebagai suatu persepsi bagaimana banyaknya tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan sumber daya (resources) tertentu. Dalam hal ini, jangka waktu untuk menyelesaikan tugas badan adhoc telah ditetapkan dalam Undang-undang dan PKPU yang mengatur tentang jadwal tahapan Pemilu.
Tugas utama PPK dan PPS lebih pada tahapan pembentukan badan adhoc, penyusunan daftar pemilih, distribusi logistik Pemilu, dan rekap hasil Pemilu. Sementara tugas lainnya lebih bersifat fasilitatif dan dukungan, seperti fasilitasi kampanye, fasilitasi pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS, dan sosialisasi Pemilu. Tugas-tugas ini merupakan pekerjaan yang memiliki tenggat waktu yang cukup panjang, yakni dikerjakan dalam jangka lebih dari 1 (satu) hari. Dukungan resources PPK dan PPS, baik SDM, anggaran, maupun resources lainnya, sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas.
Tugas Pantarlih lebih fokus pada 1 (satu) pokok pekerjaan, yakni pemutakhiran data Pemilih, dengan jangka waktu pengerjaan sekitar 1 (satu) bulan. Dukungan resources Pantarlih sudah cukup memadai, contohnya alat kerja yang telah disediakan dan Pantarlih tinggal melaksanakan.
Tugas KPPS merupakan pekerjaan badan adhoc yang paling berat. Dalam masa kerja 1 (satu) bulan, biasanya waktu ini terbagi dalam 4 (empat) masa pekerjaan, yakni masa Bimtek di Minggu I, masa penyebaran formulir pemberitahuan/undangan Pemilih di Minggu I dan Minggu II, dan masa pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan puncak pekerjaan KPPS. Minggu terakhir KPPS bertugas untuk menyelesaikan laporan administratif dan keuangan.
Masa Bimtek merupakan masa persiapan yang tidak banyak menguras sumber daya KPPS. Masa undangan Pemilih mulai menguras energi dengan pekerjaan manual tulisan tangan dan keliling dari rumah ke rumah dalam waktu biasanya 2 (dua) minggu. Masa puncak yang paling sibuk adalah saat penyiapan TPS dan pengamanan logistik TPS yang dilakukan pada H-1 pemungutan suara hingga pelaksanaan hari pemungutan suara dan penghitungan hasil perolehan suara, yang dapat berjalan selama 36 (tiga puluh enam) jam tanpa henti (rapat pemungutan suara dimulai pukul 7.00 serta penghitungan suara dilakukan paling lambat hingga pukul 23.59 dan dapat diperpanjang hingga 12 (dua belas) jam). Dengan demikian, masa puncak KPPS ini berjalan selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa henti atau 54 (lima puluh empat) jam tanpa henti.
Jika dibuat skala beban kerja badan adhoc, maka beban kerja paling mudah adalah sebagai Pantarlih, dimana resources Pantarlih sangat memadai dan tugas yang tunggal untuk melaksanakan coklit. Beban kerja PPK dan PPS berada pada skala sedang, dimana tugas-tugasnya yang membutuhkan waktu yang panjang namun didukung resources yang cukup. Beban kerja KPPS berada pada skala yang berat, bahkan sangat berat, jika mengingat tekanan politik dan jam kerja yang tanpa henti pada masa penghitungan suara.
Faktor yang Membebani
Terdapat beberapa faktor lain yang menjadikan tugas badan adhoc Pemilu dan Pemilihan lebih berat, yakni banyaknya jenis Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan secara serentak, kerawanan Pemilu dan Pemilihan yang menuntut ketelitian dan kecermatan badan adhoc, tekanan Politik baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi suasana kebatinan badan adhoc, dan keterbatasan waktu untuk menyelesaikan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan dengan sebaik-baiknya.
Keserentakan Pemilu/Pemilihan
Format keserentakan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 menghasilkan Pemilu 5 Kotak Suara yang sangat berat, dan Pemilihan 2 Kotak Suara yang jauh lebih ringan. Pemilu 5 Kotak sangat berat karena memaksa jam kerja badan adhoc yang sangat panjang.
Tuntutan Ketelitian dan Kecermatan
Walau dalam waktu yang melelahkan, badan adhoc tetap dituntut untuk senantiasa teliti dan cermat dalam melakukan setiap tugasnya dalam seluruh jenis Pemilu, yang seringkali dilakukan saat larut malam dan dalam kondisi tubuh yang tidak dapat lagi fokus.
Tekanan Politik
Di sela-sela kesibukan tugasnya, tidak jarang perwakilan/saksi peserta Pemilu masih mengajukan keberatan kepada badan adhoc. Tentu saja, hal ini semakin memberikan tekanan tambahan kepada badan adhoc.
Waktu Terbatas
Ada idiom yang cukup populer di kalangan Penyelenggara Pemilu, bahwa 24 jam dalam sehari rasanya tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas kepemiluan yang dituntut dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal. Hal ini terjadi pula di badan adhoc.
Refleksi Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
Persyaratan Badan Adhoc
Dalam regulasi pembentukan badan adhoc Pemilu 2019 (PKPU No. 3 Tahun 2018 diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018), persyaratan badan adhoc secara umum ditujukan untuk mencari SDM badan adhoc yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan. Kompetensi dan kapasitas SDM badan adhoc belum diperhatikan dengan serius. Hal ini tampak pada 2 (dua) hal, yakni alternatif persyaratan pendidikan dapat diganti dengan kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung (calistung), dan alternatif persyaratan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari puskesmas, alih-alih rumah sakit.
Regulasi persyaratan yang serupa masih diterapkan dalam Pemilihan 2020 (PKPU No. 3 Tahun 2015 dibuah dengan PKPU No. 12 dan 13 Tahun 2017). Namun terdapat perbedaan pada persyaratan usia dan kesehatan Pantarlih dan KPPS. Pada Pemilihan 2020, dimana pandemi Covid-19 sedang melanda, Pantarlih dan KPPS dipersyaratkan berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, serta tidak memiliki penyakit penyerta/komorbiditas (PKPU No. 6 Tahun 2020 diubah dengan PKPU No. 10 dan 13 Tahun 2020). Meskipun ketentuan ini dibuat bukan sebagai evaluasi Pemilu 2019, melainkan sebagai respons atas kejadian bencana nonalam Covid-19, namun hal ini merupakan langkah baik dalam perbaikan manajemen SDM badan adhoc.
Dalam regulasi pembentukan badan adhoc Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020, tampaknya KPU pesimis terhadap antusiasme para pendaftar badan adhoc saat seleksi dilakukan secara terbuka, sehingga perlu menetapkan ekspektasi yang rendah terhadap kompetensi dan kapasitas SDM badan adhoc. Atau barangkali KPU menyadari bahwa badan adhoc seringkali minim regenerasi sehingga tidak berharap banyak kepada atensi para pendaftar non pengalaman kepemiluan.
Kasus Kecelakaan Kerja Badan Adhoc
Jumlah badan adhoc yang sakit dan meninggal serta mendapatkan santunan kecelakaan kerja pada Pemilu 2019, berdasarkan data Kemenkeu adalah sebanyak 798 orang yang sakit dan 722 orang yang meninggal. Dari jumlah tersebut, dapat dirinci sebagai berikut:
No
Badan Adhoc
Jumlah Sakit
Jumlah Mening gal
Jumlah
1.
PPK
63
21
84
2.
PPS
128
74
202
3.
KPPS
546
414
960
4.
Linmas
61
213
274
Total
798
722
1520
Sementara itu, jumlah kasus kecelakaan kerja badan adhoc pada Pemilihan 2020 mengalami penurunan. Penurunan kasus disebabkan adanya perbaikan regulasi persyaratan Pantarlih dan KPPS terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 dan beban kerja Pemilihan 2020 yang umumnya hanya 1 Kotak Suara. Menurut data KPU, tercatat jumlah kasus meninggal sebanyak 117 orang dan kasus sakit 153 orang.
Pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, angka kasus kecelakaan tetap besar, namun angka kasus meninggal menunjukkan pengurangan jumlah kasus. Terdapat 181 orang yang meninggal, angka ini menurun dibandingkan Pemilu 2019. Namun angka sakit meningkat tajam pada jumlah 4.773 orang yang sakit. Jumlah ini mungkin disebabkan oleh beban kerja yang sangat berat dan adanya SDM baru yang membutuhkan waktu lebih dalam memahami proses dan substansi pekerjaan yang berpengaruh ke kesehatannya.
Berikut rincian data badan adhoc Pemilu 2024 yang mengalami kecelakaan kerja:
No
Badan Adhoc
Jumlah Sakit
Jumlah Mening gal
Jumlah
1.
PPK
166
6
172
2.
PPS
786
23
809
3.
KPPS dan Linmas
3.821
152
3.973
Total
4.773
181
4.954
Pada Pemilihan 2024, angka ini mengalami tren yang positif dengan jumlah badan adhoc yang meninggal sejumlah 183 orang dan yang sakit sebanyak 479 orang.
Faktor yang Mendukung
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan evaluasi manajemen SDM badan adhoc Pemilu dan Pemilihan 2024 adalah adanya perubahan dalam regulasi persyaratan badan adhoc Pemilu dan Pemilihan 2024, pemberian bimtek kepada badan adhoc dengan metode training of trainers, penggunaan teknologi informasi pada seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta peningkatan jumlah honorarium badan adhoc.
Perbaikan Regulasi
Berdasarkan ketentuan Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 52 PKPU No. 22 Tahun 2022, pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon badan adhoc. Kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian badan adhoc selanjutnya berusaha dimanifestasikan ke dalam persyaratan badan adhoc pada Pasal 35. Ketentuan terbaru mengenai batas usia badan adhoc dituangkan dalam Pasal 35 ayat (2), yang berbunyi
“Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.”
Penjelasan persyaratan-persyaratan ini dirinci dalam Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 sebagai berikut:
Menggunakan teknologi informasi SIPOL dan SIAKBA untuk verifikasi data keanggotaan Partai Politik calon badan adhoc, untuk menilai kemandirian
Mengutamakan calon badan adhoc yang tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) atau tidak memiliki riwayat penyakit: hipertensi, diabetes meilitus, tuberkulosis, stroke, kanker, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit paru, dan penyakit imun
Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik mencantumkan atau dilampiri hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol
Alternatif kapasitas pendidikan dengan calon badan adhoc yang mampu Calistung masih diberlakukan
Terlihat bahwa regulasi terbaru mengedepankan SDM badan adhoc yang memiliki kondisi kesehatan yang prima untuk menghadapi tugas-tugas Pemilu yang tidak mudah. Selain itu, persyaratan batas usia KPPS telah mendorong pembentukan badan adhoc diisi oleh generasi muda, bukan lagi generasi tua yang tidak hanya rawan dalam hal kesehatan, namun juga memiliki kecenderungan tidak adaptif terhadap perubahan regulasi dan penggunaan teknologi informasi.
Bimtek Badan Adhoc
Bimtek dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas badan adhoc dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bimtek dilakukan dengan metode training of trainers (ToT), dengan pemberian modul pelatihan yang jelas dan mudah dipahami. Frekuensi pemberian bimtek dan ToT kepada badan adhoc akan sangat berpengaruh terhadap kompetensi badan adhoc dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif.
Penggunaan Teknologi
Sistem informasi digunakan di seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, terutama yang berkaitan langsung dengan tugas KPPS adalah SIREKAP. Penggunaan SIREKAP dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS membantu meringankan tugas badan adhoc dalam rekap hasil Pemilu dan Pemilihan.
Lebih lanjut, SIREKAP dirancang untuk menghasilkan dokumen digital salinan berita acara dan sertifikat penghitungan hasil perolehan suara. KPPS tidak lagi mengerjakan tugas yang melelahkan untuk menyalin berita acara dan sertifikat secara manual dengan tulisan tangan sebanyak jenis Pemilu dikalikan jumlah peserta Pemilu. Pada Pemilu dan Pemilihan 2024, salinan diberikan kepada peserta Pemilu dalam bentuk dokumen digital atau hasil penggandaan dengan mesin pengg